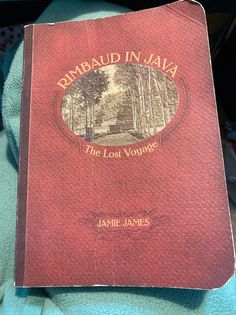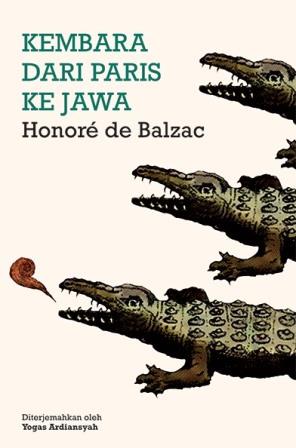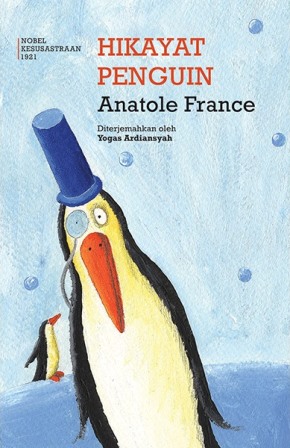Wawancara di bawah ini, diambil dari Grup Facebook Apresiasi Sastra (APSAS) Indonesia
Sigit Susanto: “Buat Mas Yogas Ardiansyah, saya sangat senang jika karya-karya sastra dari 2 bangsa, Prancis dan Jerman bisa dialihbahasakan ke bahasa kita. Alasannya, kedua bangsa bersebelahan itu banyak sekali melahirkan peraih nobel dan karya sastranya betul-betul menjadi inspirasi pengarang lain. Saya berkenalan dengan sastra Prancis dengan membaca Education Sentimentale, juga Perjalanan ke Mesir – Flaubert, disusul Siang dan Malam di Amerika – Simone de Beauvoir, Pest-nya Camus. Pertanyaan saya, 1). Apakah kemudahan mengalihbahasakan ke bahasa kita, mengingat bahasa Prancis mirip bahasa Jerman yang ada subjek hirarkis antara kamu dan Anda? 2). Apakah lulusan sarjana sastra Prancis kita nasibnya seperti bahasa asing lain yang enggan menekuni di bidang terjemahan sastra? 3). Apa kekhasan sastra Prancis yang membedakan dari pengarang belahan bangsa lain? 4). Semoga Moooi Pustaka kelak menerjemahkan karya Edouard Dujardin yang berjudul Les lauriers sont coupes. Buku ini sangat berpengaruh besar di tahun 1920-an di Paris, karena dipakai menutup novel Ulysses karya James Joyce pada bab 18 (akhir), dikenal sebagai ‘monolog-interior’, kala itu Joyce membeli di kios, sebagai buku yang tidak dikenal, akhirnya buku ini diburu dan Dujardin masih hidup berterima kasih kepada Joyce. 5). Mas Warih Wisatsana mungkin bisa sharing, berbagi kisah sebagai editor karya Sartre, terjemahan Bli Made di Bali alias Jean Couteau. Terima kasih.
Yogas Ardiansyah: “Pak Sigit, saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu atas kesempatan buat saya berbagi pengalaman dalam menerjemahkan, khususnya dari bahasa Prancis menuju bahasa Indonesia dalam forum ini. Boleh jadi kita baru berkomunikasi bulan-bulan belakangan ini. Tapi sebetulnya, saya sudah kenal dan ikut acara njenengan sejak sekitar sepuluh tahun lalu. Suatu kali, seorang kawan mengajak saya dolan ke Boja, ke rumahnya, sebab dia bilang, di dekat dia tinggal, ada sebuah perpustakaan yang rutin mengadakan acara literasi. Dan malam itu, dia bilang akan hadir Pak Ahmad Tohari, begawan sastra kita yang bermukim di Kabupaten Banyumas. Saya setengah tak percaya, sebetulnya. Bagaimana mungkin sebuah perpustakaan desa bisa mendatangkan seorang Tohari. Tapi toh saya tetap berangkat. Itung-itung jalan-jalan. Maka sorenya kami menempuh perjalanan dari Kampus Unnes di Gunungpati menuju Boja, melintasi jalan naik-turun, berkelok-kelok, menyuguhkan panorama bukit, hutan, sawah dan pemukiman silih berganti. Jauh sekali, rasanya. Tapi menyenangkan, suasananya. Yang lebih menakjubkan lagi, di perpus itu -sebuah rumah tinggal kecil, rumah keluarga Pak Sigit, yang kamar-kamarnya disulap menjadi tempat rak buku dan halaman sampingnya menjadi tempat pertemuan sederhana, telah ramai orang berkumpul. Meriah. Bukan hanya anak-anak muda, tapi juga orang-orang tua, yang rasanya amat sangat jarang terlibat dalam acara demikian. Hingga tiba waktunya, sosok Ahmad Tohari itu betul-betul muncul, tersenyum ramah ke arah kami yang menunggunya. Berkemeja batik coklat, sang pengarang itu segera menyatu dan membaur bersama kami, bercerita, menjawab pertanyaan teoretis ataupun pertanyaan iseng yang diajukan kepadanya. Saya hanya melongo saja, tak bertanya, sebab masih belum percaya di depan saya ada Tohari sang idola. Hingga acara selesai, saya tak berani bahkan untuk sekadar menyapanya. Demikianlah. Acara itu menjadi awal saya untuk mengikuti acara di Pondok Baca Guyub, yang dikemudian hari juga mendatangkan Remy Silado dan almarhum Pak Iman Budhi Santosa. Untuk kenangan masa itu, saya juga mengucapkan terima kasih Pak Sigit.
Dan berikut jawaban atas beberapa pertanyaan Pak Sigit.
1). Sejujurnya proses penerjemahan yang saya lalui, lebih berisi kesukaran daripada kemudahan. Betapa tidak? Saya hanya seorang pembelajar bahasa asing itu di kampus, belum pernah hidup dan bergaul dengan orang serta budayanya, dan langsung berhadapan dengan seorang Anatole France. Singkat cerita, hanya modal nekat dan tekun saja, saya bisa mengatasi hambatannya satu demi satu. Atau kebetulan, sebelumnya saya pernah membaca roman klasik Prancis -bandingkan dengan Pak Sigit yang awal mula sudah membaca penulis kontemporer macam Flaubert, Jean Paul Sartre, dan Simone de Beauvoir. Sayangnya, saya “babar blas” tak mengerti bahasa Jerman, jadi tak bisa membandingkannya dengan bahasa Prancis. Prancis memang mengenal tu (orang kedua tunggal) dan vous (orang kedua jamak, atau orang kedua tunggal bernuansa resmi ataupun kesopanan/la politesse). Kau, dan Anda, secara sederhananya dalam bahasa Indonesia, Kowe dan Panjenengan, dalam bahasa Jawa kita. Ada pergeseran pemakaian Tu (ber kau-kau) dan Vous (ber Anda-Anda). Sekarang, Tu dipakai dalam konteks akrab, dewasa kepada yang lebih muda, satu keluarga, dan Vous, sebaliknya. Tapi dalam beberapa roman lama, suami-istri (pasangan) ternyata juga memakai Vous -padahal akrab dan keluarga. Juga ada sedikit perbedaan pemakain kesopanan : bila anak kepada orang tua di Jawa memakai bentuk sopan, maka di Prancis, anak dan orang tua memakai bentuk akrab, ber tutoyer, ber kau-kau. Demikianlah, konteks hirarkis dalam bahasa ternyata tak selalu sama dan sebanding. Bagaimana dengan bahasa Jerman? Meski Mbak Tiya dan Pak Sigit saling bertukar jawab dalam sesi lalu, toh saya kurang terlalu mengerti juga.
2). Ini pertanyaan terhadap situasi yang Pak Sigit sudah pirsa sendiri. Kenyataannya memang demikian : sedikit peminat pada bidang penerjemahan, artinya yang mau menerjemahkan. Bahkan meski susastra Prancis menawarkan lautan teks dan pemikiran yang semestinya bisa digali. Kita bisa mendapati beragam penyebab, tapi saya meraba wajah sendiri saja : bahwa duduk empat-lima jam sehari bergelut dengan teks dan kamus bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah dikerjakan. Kabar baiknya, ternyata ada juga satu-dua kawan yang semangat dan antusias sekali melakulannya. Terutama lagi, sebisa mungkin menerjemakan dari bahasa sumbernya. Bersama kawan-kawan ini, saya merasa tidak sendiri, sekaligus terus saling menyemangati. Semoga habitat kecil ini bisa berkembang sebagaimana mestinya.
3). Dari sisi kebahasaan, Prancis menawarkan bentuk tuturan dan narasi yang sama sekali berbeda dengan cara orang Indonesia bercerita dan menulis. Bagi sesama orang bangsa Eropa, mungkin tidak masalah. Tapi bagi pembaca Indonesia, kalimat panjang berliku bisa jadi menyulitkan, bagi yang belum terbiasa. Seperti yang Pak Sigit sudah tahu, ciri khas susastra bangsa Prancis adalah, salah satu dan bagi saya yang terutama, adalah keberanian menabrak dan mempertanyakan, bahkan terhadap hal yang bagi sebagian orang amat sakral, agama misalnya, seperti yang diungkapkan Mbak Ida tempo hari. Selain itu, sesuai filosofi tentang ke-aku-annya, susastra Prancis meletakkan akal dan logika di atas segalanya, meski tak seluruhnya, seperti ungkapan Rene Descartes yang dikutip di mana-mana : je pense donc je suis.
4) Amin, semoga, Pak. Menurut Ketua Genk-nya, Moooi punya banyak calon naskah berbahasa Prancis yang ingin dialihbahasakan. Ini tentu saja kabar baik, artinya akan peluang bagi kawan-kawan yang berminat menerjemahkan. Lalu yang ke 5). Dan lagi-lagi saya hanya bisa mengucapkan terima kasih, atas kebaikan hati Pak Sigit, saya bisa sekadar berkenalan dengan Pak Jean Couteau. Sesekali kami bertukar sapa. Beruntung saya bisa bisa belajar dari tokoh seperti beliau. Terima kasih.”
Sigit Susanto: “Merci, matur nuwun, terima kasih banyak.”
***
Sigit Susanto: “Pertanyaan terakhir jelang lebaran: Apakah kisah penyair klasik Rimbaud (Di Indonesia bisa jadi nama Ribut) ini benar-benar pernah disewa sebagai serdadu oleh pemerintah Belanda untuk ditempatkan di Indonesia. Pada buku ini disebut Mas Ribut pernah latihan baris-berbaris dari Muncul ke Salatiga. Menurut sampean, apakah cerita ini benar adanya? Jika tidak, kenapa Kedubes Prancis di Jakarta kabarnya saat ultah Prancis memakai bekas rumah Mas Ribut ini di Salatiga. Kalau Balzac in Java yang ditulis oleh penulis yang sama dengan Ribut ing Jowo, Balzac sebatas fantasi. Terima kasih banyak.”
Yogas Ardiansyah: “Rimbaud jadi Ribut. Cocok, Pak. Atau bisa juga Rembo. Tapi agak tidak cocok, sebab sosok Rambo itu tentara gagah berani, sedangkan Rimbaud tentara cemen, desersi pula. Namanya juga pelokalan, pasti ada mleset-mlesetnya. Soal Rimbaud pernah mampir di Salatiga, rasanya saya pikir betul. Seperti yang Njenengan bilang, pemerintah Prancis sampai perlu memasang plakat di gedung yang disinggahinya. Yang saya tak faham, mengapa hanya di Salatiga -hanya dua minggu saja pula. Logikanya, pasti dia juga pernah ke Semarang, atau Magelang atau Jogja (lewat mana kalau ke Salatiga selain tiga kota besar ini di masa itu). Ini saya yang tak tahu, dan jujur saja saya belum membaca buku itu. Saya juga tak banyak membaca syair Rimbaud, kecuali satu puisi berjudul Perahu Oleng itu. Mungkin kita perlu belajar pada Pak Jos Wibisono yang saya ingat pernah menulis panjang soal Rimbaud di Jawa, juga pada seorang penulis asal Sulsel yang pernah meneliti kehidupan Rimbaud -saya lupa namanya. Tetapi, membahas Rimbaud dan Balzac, terlepas perkara siapa yang pernah benar2 ke Jawa dan siapa yang ngayal saja, bahwa Nusantara sudah memikat minat orang Eropa sejak dulu kala. Kalau dibahas lebih lanjut, kita akan masuk ke dalam beragam kajian, mulai dari Orientalisme hingga Kolonialisme sekaligus Post-nya, dan itu akan menjadi diskusi yang puuuaaanjang. Alhamdulillah. Lagi-lagi, saya hanya bisa mengucapkan terima kasih banyak, Pak Sigit. Je souhaite un tres bon week-end pour vous et votre famille, en attendant la fin de Ramadan Kareem et L’Eid Mubarak qui s’approche. Merci, Monsieur.”
Sigit Susanto: “Kebetulan kedua buku Balzac dan Ribut di Jawa itu sudah aku baca. Celakanya kedua buku itu tidak dijual di toko buku kita di kota-kota besar, melainkan di toko buku asing yang berada di bandara Internasional seperti di Bali dan Yogyakarta. Pada buku Balzac ini jelas disebutkan, bahwa Balzac sekadar membayangkan perempuan-perempuan Jawa yang dianggap eksotis pada zaman itu. Jadi memang Balzac di Jawa sebatas fantasinya, tidak seperti Rimbaud. Nah, siapa penulis 2 buku itu yang diterbitkan penerbit yang sama di Singapura, seorang expatriat yang punya kafe di Kuta, Bali. Ia pernah ikut acara Ubud Writers dan menerjemahkan 1 cerpennya Niduparas Erlang. Jadi Niduparas Erlang mungkin bisa cerita pertemanannya dengan penulis. Tabik.”
Yogas Ardiansyah: “Dalam buku itu Balzac tak melulu bicara perempuan, Pak Sigit. Dia juga ngomong panjang soal pohon Upas, yang menurut saya malah bagian yang paling seru. Yang jarang diungkap juga adalah tradisi Rampog, adu manusia melawan harimau. Dia singgung pula tabiat lelaki jawa yang ngamuk setelah mabuk ciu atau candu. Balzac juga sedikit cerita soal lanskap alam Jawa, kisah lumayan panjang mengenai gelatik, juga teh dan kopi di Jawa, dan soal buaya, kawanan monyet beserta pawang2nya. Tapi yang paling menarik perhatian tentu saja adalah soal perempuan. Maka seolah eksotika Jawa adalah tentang perempuannya. Lumrah saja. Dia sendiri bilang, bahwa kenikmatan surgawi pria Eropa menurutnya adalah, rebahan di teras terbuka ditemani semilir angin tropis dan pemandangan hamparan padi, dihibur nyanyian gelatik, sambil menyeruput teh, dan tentu saja, dalam dekapan perempuan Jawa. Bajinguk sekali dia menghayal. Oh ya, Balzac juga menyinggung kelakuan Tionghoa pedagang yang mencurangi pelanggannya. Dan, semua cerita tadi tidak sepenuhnya khayalan. Balzac dibantu oleh catatan perjalanan yang dipunya oleh Grand Duc de Besancon, kalau saya tak keliru. Sedang Rimbaud, hehe, begitulah, saya belum membacanya secara detail, jadi tak bisa banyak bercerita. Trims, Pak.”
Sigit Susanto: “Betul, Balzac tidak melulu bicara tentang perempuan Jawa, tapi perempuan Jawa dalam imajinernya. Sumber lain ternyata ia punya penerbitan yang kemudian bangkrut. Sejalan dengan itu Mark Twain juga punya penerbitan dan bangkrut. Twain keliling Eropa sambil bicarakan sastra dan kumpulkan dana atas kebangkrutannya itu. Lawatannya ke Eropa menjadi buku berjudul Bummel durch Europa (Kluyuran sepanjang Eropa) termasuk mampir ke kota Lucern, Swiss sempat mendaki gunung Rigi di tepi danau Zug, dimana aku tinggal kini, sempat ia kesasar. Kayaknya sastrawan merangkap punya penerbitan diikuti di kita, Eka Kurniawan dengan Moooinya, Puthut EA dengan Mojoknya, Anton Kurnia dengan Penerbit Bacanya, Kian Santang dengan Circanya. Majulah sastra kita.”
Yogas Ardiansyah: “Amin. Terima kasih, Pak Sigit.”
***
Karya-karya terjemahan Yogas Ardiansyah: